SEKSUALITAS INFANTIL FREUD
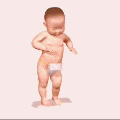

Mengutip pendapat Peter Gay bahwa “telah menjadi takdir Freud untuk menggelisahkan kelelapan umat manusia”.[1] Kita ketahui bahwa Sigmund Freud menjadi sorotan banyak kalangan ketika dia menguraikan mengenai alur tahapan perkembangan kepribadian via seksualitas. Freud menyangkal bahwa dorongan seksual tidak berawal pada masa pubertas namun sedari bayi. Dan seksualpun menjadi penggerak dalam keseharian manusia. Hal ini kemudian menjadi trendsetter corak terapi dan tafsiran kepribadian dalam fenomena kehidupan. Tak ayal kemudian dengan cepat banyak para Psikiater yang bergabung dalam mazhab psikodinamika Freud. Seperti Carl Gustave Jung dari Zurich, A.A Brill dari New York, Sandor Verenzci dari Budapest, Karl Abraham dari Berlin dan Alfred Adler dari Wina.[2]
Perbincangan mengenai seksualitas ialah titik sentral dalam melihat kepribadian futurutif manusia. Maka itu Freud kemudian menjelaskan mengenai perkembangan psikoseksual. Penjelasan ini terus berlanjut dan menjadi ruang kritik bagi pengikut Freud, walaupun Freud telah bersikap otoriter pada psikiater-psikiater yang mengkritiknya. Tahapan perkembangan seksual tersebut meliputi tahap oral, anal, falik, laten dan genital. Salah satu fase dari psikoseksualnya itu adalah fase phalik, fase dimana kenikmatan seksual berada pada alat kelamin dan berlangsung ketika anak berumur sekitar 3 tahun sampai 5 tahun. Alat kelamin menjadi lebih peka terhadap stimulasi, sehingga memberikan sensasi-sensasi yang nikmat bila distimulasi. Perlu diketahui bahwa seorang anak di fase phalik yang melakukan masturbasi, bukanlah didorong oleh suatu pikiran yang porno ataupun moralitas yang rendah. Mereka melakukan itu semata-mata sebagai reaksi alamiah, karena alat kelamin mereka menjadi peka (“gatal”) dan ingin disentuh. Oleh karena itu, masturbasi yang dilakukan di fase ini bersifat Innocent.[3]
Akan tetapi, apakah temuan Freud berhenti di situ saja? Tentu tidak, temuan Freud tidak berakhir di situ. Adalah kompleks oedipus[4] dan kompleks kastrasi yang juga menyertai dinamika fase tersebut. Dan berkontribusi dalam pengisian ruang determinisme historis khas psikoanalisis.
Mainstream seksualitas alat kelamin dalam form kenikmatan masturbasi serta kehidupan fantasi anak yang menyertai aktivitas auto-erotik, membuka jalan bagi timbulnya kompleks oedipus. Secara singkat kompleks oedipus meliputi kateksis seksual terhadap orangtua yang berlainan jenis serta kateksis permusuhan terhadap orangtua sejenis.[5] Efek dari timbulnya kompleks oedipus adalah anak menganggap orangtua sejenis sebagai penghalang cintanya kepada orang tua lain jenis yang dicintai. Dan efeknya ini akan menyebabkan timbulnya kompleks kastrasi berupa ketakutan akan pengebirian alat vital anak. Yaitu dalam bentuk kecemasan terhadap pemotongan alat vital atau kehilangan penis yang notabene sebagai sumber kenikmatan seksual atau eregoneus zone.
Timbulnya kompleks oedipus dan kompleks kastrasi pada anak perempuan berbeda dengan anak laki-laki. Pada anak perempuan kompleks kastrasi terjadi lebih awal ketimbang kompleks Oedipus. Pada mulanya anak perempuan mencintai Ibu, kemudian mengganti obyek cintanya dengan Ayah. Kejadian ini, praktis didasarkan pada sikap kekecewaan anak perempuan kepada Ibu atas alat kelaminnya yang tidak seperti penis pada anak laki-laki dengan bentuk menonjol dan panjang. Fenomena ini juga disebut sebagai penis envy atau Iri Penis. Anak perempuan juga menganggap bentuk penis yang apa adanya itu sebagai simbol keagungan. Ibu dicap sebagai “dalang” atas takdir bentuk vagina anak perempuan, karena Ibulah yang melahirkannya. Dalam perkembangannya, anak akan mencintai sang ayah, karena Ayah mempunyai alat kelamin yang didamba-dambakan anak perempuan.
Yang menarik dari konten kompeks oedipus dan kompleks kastrasi ialah dimana disinilah sebuah fase perkembangan kepribadian muncul dalam skema keluarga. Freud menjelaskan, pada saat anak-anak berikutnya lahir, kompleks oedipus menguat dan meluas menjadi Family Complex.[6] Dimana perasaan benci berekspansi kepada anak yang baru lahir. Namun pada akhirnya seorang anak laki-laki mungkin akan menjadikan adik perempuannya sebagai objek cinta mengantikan Ibunya yang tidak dapat dipercaya. Begitupula dengan anak perempuan yang akan menjadikan kakak laki-lakinya sebagai objek Cinta yang tidak mempercayai sang ayah.[7] Inilah wujud dari potensi proses kepribadian yang ramai dan dinamika seksualitas yang menarik dalam pemikiran Freud. Selain itu pula super ego memiliki benih yang tersimpan dalam rahim resolusi kompleks oedipus dan kompleks kastrasi, seperti yang digadangkan Reuben Fine.[8] Final dari dua kompleks inipun menjadi rangkaian dalam membentuk fondasi identitas seksual yang kokoh, dengan catatan kedua kompleks ini teratasi.[9] Apapun pertarungan dari kedua kompleks ini, bila tidak teratasi justru menjadi wujud ketidakmandirian seorang anak hingga dewasa. Bagi seseorang anak laki-laki, tugasnya termasuk membebaskan keinginan libidonya terhadap sang Ibu, agar dapat menggunakannya dalam usaha mencari objek cinta eksternal dalam kehidupan nyata, juga untuk mendamaikan dirinya dengan sang ayah jika dia masih bermusuhan. Namun, pada orang berpenyakit neurosis, pemisahan terhadap orang tua tidak terjadi sama sekali. Jika itu yang terjadi, Freud mengatakan, anak laki-laki selama hidupnya akan tunduk pada Ayahnya[10].
Hal lain yang menjadi kontroversi dari pemikiran seksualitas Freud adalah- dan menjadi titik sentral- seksualitas atau kebutuhan jasmani sebagai penggerak dalam kehiduapan sehari-hari, dan apabila tidak tersalurkan maka manusia cenderung memakai mekanisme pertahanan dirinya yang semata-mata untuk mengurangi ketegangan.
Lebuih dari itu kandungan lain dari seksualitas Sigmund Freud yaitu kaitannya dalam wilayah konstruksi sosial. Moira Gattens seperti dukitip oleh Rahmat Hidayat pernah berujar bahwa insting seksual, misalnya, tidak muncul dalam sifat bawaan atau sifat alamiah, tetapi terkonstruksi melalui pelbagai sosialisasi praktik seksual tertentu di luarnya secara kultural dan historis.[11] Selain itu pula, wilayah super ego sebagai saham kompleks oedipus dan kompleks kastrasi, sebenarnya lebih sebagai bentuk internalisasi nilai sosial yang diwakili oleh Ayah. Rahmat Hidayat lalu menyimpulkan, bahwa psikoanalisis menjadi penting bagi kritik feminis karena ia menyediakan kerangka kerja yang mampu mengartikulasikan konteks sosial-kultural dari determinasi-determinasi biologi. Fokus penyelidikannya lebih pada proses-proses dimana tubuh, bersama apapun kapasitasnya, terproduksi secara seksual sebagai tubuh yang terseksualkan dalam situasi historis tertentu.[12]


Komentar
Posting Komentar